Reshuffle Kabinet: Antara Idealisme danPragmatisme
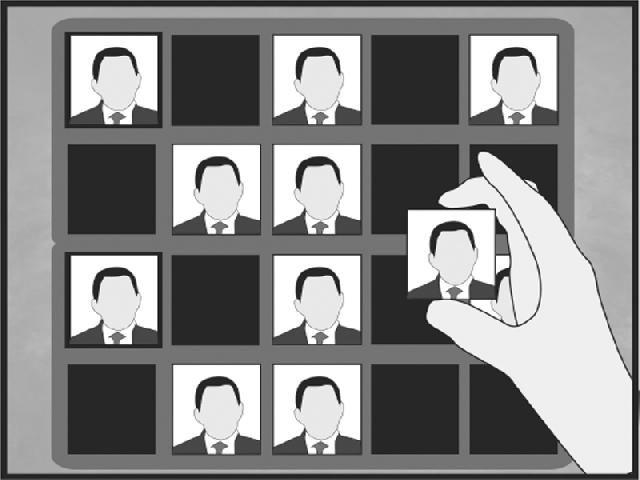
Akhirnya desas-desus pergantian Kabinet Jokowi terjawab sudah. Rabu (27/07), Presiden Joko Widodo mengumumkan perombakan kabinetnya. Sebelumnya, enam bulan terakhir publik disibukkan dengan prediksi siapa-siapa saja yang akan menghiasi wajah kabinet pasca bergabungnya beberapa partai politik ke kubu Jokowi.
Dalam perombakan kabinet kali ini, ada 13 posisi menteri dan setingkat menteri yang diganti. Sembilan adalah wajah-wajah baru dan empat hanya bertukar posisi. Mereka yang berganti posisi ialah Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan digantikan Wiranto. Luhut Binsar Pandjaitan
menduduki Menko Maritim dan Sumber Daya yang sebelumnya dijabat Rizal Ramli. Bambang Brodjonegoro yang sebelumnya Menteri Keuangan menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Sofyan Djalil yang sebelumnya menjadi menteri PPN/Kepala
Bappenas menjadi Menteri ATR/Kepala BPN menggantikan Ferry Mursyidan Baldan yang keluar dari kabinet dan Thomas Trikasih Lembong sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang sebelumnya menjabat Menteri Perdagangan.
Sedangkan wajah-wajah baru adalah Wiranto yang menempati posisi Menko Polhukam, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Muhadjir Effendy menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Enggartiasto Lukita sebagi Menteri Perdagangan, Asman Abnur menjadi MenPAN-RB, Archanda Tahar sebagai Menteri ESDM, Airlangga Hartarto men jadi Menteri Perindustrian, Eko Putro Sandjojo menjabat Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Desa dan Transmigrasi serta Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan.
Masuknya sejumlah wajah baru dan bertukarnya posisi beberapa menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Tentu sebagai nakhoda, Jokowi ingin “anak buah kapalnya” orang-orang yang mumpuni di bidangnya, agar perjalanan kapal besar yang bernama Indonesia selamat dan terus melaju di samudera yang kian hari gelombangnyakian besar. Dan dalam memilih kabinet seorang presiden dihadapkan antara idealisme yang dianut dengan pragmatisme politik. Sehingga terkadang pragmatisme mengalahkan idealisme yang dijunjung dan dianut oleh sang presiden. Aroma inilah yang menurut hemat penulis menyelubungireshuffle jilid dua Kabinet Jokowi-JK.
Jauh sebelum terpilih menjadi Presiden, Jokowi mengatakan ia akan memilih dan menempatkan orang orang yang profesional dalam kabinetnya. Bahkan ia menolak dengan tegas dan lugas bahwa kepemimpinannya nanti jauh dari politik transaksional dan intervensi politik.
Kabinet bagi Jokowi bukanlah ajang bagi-bagi kursi, tapi tempat mengabdi dan memberikan kontribusi nyata pada negeri. Namun seiring perjalanannya, idealime itu, kini mulai tergilas oleh pragmatisme politik kekuasaan. Sulit untuk mengatakan bahwa kabinet era Jokowi bukan bagi kursi. Buktinya, parpol yang mendukung Jokowi semua kebagian kursi, malah reshuffle jilid dua ini terlihat untuk mengakomodasi partai yang merapat ke Istana seperti PAN dan Golkar.
Memang dalam politik, pragmatisme politik adalah bayang-bayang yang membuat idealisme kian tidak terlihat, yang akhirnya membuat idealisme itu menjadi barang lapuk yang tidak berguna dalam alam pragmatisme. Orang yang hidup dan berkutat di luar sangkar politik, akan beruar-uar dan berteriak lantang, bahwa kelak dia memimpin akan melakukan selaras dengan idealisme yang dia anut. Rupanya alam politik berbeda
dengan alam sadar kebanyakan. Dalam alam politik tidak mengenal yang namanya kawan dan musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi, dan semua dukungan politik tidak ada yang gratis bak ungkapan Milton Friedman tak ada makan siang gratis alias no free lunch.
Membaca arah reshuffle Kabinet sekarang terlihat, Jokowi sedang menyusun pondasi kekuasaannya agar kian menjangkar dan kokoh dalam
perjalanan kedepan. Hal ini terlihat dari penempatan posisi para menteri dan tokoh yang direkrut menjadi menteri. Pertama, dalam menempatkan para menteri, Jokowi kian hati-hati. Menteri yang membuat kekuasaanya kian “terdegradasi” di rotasi, seperti MenkoPolhukam Luhut Binsar Pandjaitan. Keberadaan Luhut dulunya sebagai Kepala Staf Kepresidenan juga melahirkan“masalah” dan dilihat matahari kembar dengan JK. Kemarin dengan posisi Menkopolhukam dengan wewenang yang besar, membuat Jokowi terlihat dalam bayang-bayang LBP. Keputusan ini lahir tentu setelah Jokowi banyak belajar politik dalam dua tahun kepemimpinannya.
Kedua, merekrut tokoh politik yang cenderung berpihak kepadanya. Memilih tokoh dari Parpol yang sedari awal dekat dan menyokong kepemimpinannya. Seperti pemilihan Menteri Airlangga Hartarto dari Golkar kubu Agung Laksono dan juga Asman Abnur yang dekat dengan Ketua Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) yang juga politisi PAN Sutrisno Bachir. Pemilihan ini tentu agar kendali Jokowi terhadap parpol-parpol tersebut kian kuat.
Ketiga, mendepak tokoh-tokoh yang tidak punya”beking” politik, seperti Anis Baswedan, Ignatius Jonan. Mengeluarkan nama-nama yang tidak memiliki kekuatan politik tersebut menjadi pilihan mudah dan tidak memiliki resistensi yang berarti bagi perjalanan politik Jokowi. Anies yang selama ini terlihat bagus namun kerap mendapat kritikan dari publik, bisa diatasi dengan kualitas Muhadjir Efenddy yang notabene pelaku pendidikan dan juga tokoh Muhammdiyyah. Pemilihan Muhadjirpun dilihat untuk menarik dukungan dari kalangan Muhammadiyah. Sebab, ormas besar NU sudah terwakili dari beberapa orang menteri.
Dalam politik, kekuasaan adalah segalanya, dan kekuasan itu ditentukan oleh politik. Untuk itu memilih dan mengganti pion-pion politik agar punya daya dobrak yang kuat dan kekuasaannya kian mencengkram adalah hak seorang presiden. Hanya saja, jangan sampai dalam memilih tersebut lebih mengedepankan politik kekuasaan semata. Sehingga idealisme yang diusung jauh-jauh hari dan termaktub dalam Nawa Cita menjadi tertutup oleh kabut pragmatisme politik. ***
*) Alumnus Pascasarjana Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM)








