Pesantren dan Pendidikan Kita
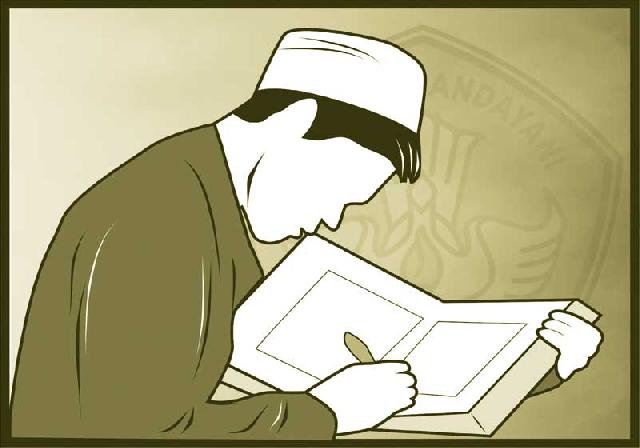
Potret pendidikan di Indonesia saat ini pantas mengusik nurani kita. Praktik pendidikan di tingkat dasar, lanjutan atau tinggi dihantui oleh komersialisasi pendidikan dan seringkali hanya berorientasi pada materi.
Mahalnya biaya pendidikan, ketimpangan antarsekolah, hingga berlomba mendapatkan gelar demi prestise (degree minded) menjadi dampak komersialisasi pendidikan (Irawaty A Kahar: 2007).
Di tingkat lanjutan dan tinggi, bahkan pendidikan berorientasi pada kebutuhan industri semata. Sekolah dan perguruan tinggi hanya menjadi pabrik bagi pelayan industri dan mendukung bangunan ekonomi semata. Generasi muda Indonesia mungkin sekali menjadi generasi yang berorientasi pada materi.
Segala pertimbangan merujuk pada untung-rugi ekonomi. Di tengah gencarnya roda-roda kapitalisme dan liberalisasi ekonomi saat ini di Indonesia, maka pendidikan bagi generasi muda telah kehilangan maknanya.
Tak heran jika kita mendengar profesor dan akademisi terjerat korupsi atau asusila. Sebagian lain generasi muda mengamini penggusuran sewenang-wenang rakyat kecil atas nama pembangunan atau mencemooh protes sopir angkutan yang tak bisa menyesuaikan dengan kemajuan teknologi.
Mereka tak mampu lagi menangkap ketidakadilan dan ketimpangan masyarakat kita. Tak hadirnya nilai-nilai dalam pendidikan kita, membuat kita harus menoleh kembali figur-figur pendiri bangsa dalam memandang pendidikan bagi generasi muda Indonesia. Salah satunya Ki Hajar Dewantara atau Suryadi Suryaningrat (1889-1959).
Selain sebagai pejuang kemerdekaan yang bergelut di dunia politik, kiprah dan visinya di dunia pendidikan patut menjadi perhatian kita. Menarik untuk memahami pendapatnya tentang pendidikan. Bagi Ki Hajar, pendidikan memiliki makna luas, tak sekadar ilmu pengetahuan belaka.
Pendidikan nasional, bagi Ki Hajar, bertujuan mengangkat derajat negara dan rakyatnya. Ki Hajar, pada 1928, sudah menegaskan bahwa pengaruh pengajaran untuk membentuk manusia merdeka, yaitu "manusia jang hidupnja lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri." (Ki Hajar Dewantara: 1962).
Ki Hajar amat menekankan, agar pendidikan, khususnya Taman Siswa yang didirikannya, dekat dengan rakyat. "Agar supaja mereka tidak hanja memiliki 'pengetahuan' sadja tentang hidup rakjatnja, akan tetapi djuga dapat 'mengalaminja' sendiri, dan kemudian tidak hidup berpisahan dengan rakjatnja.".
Dengan bercermin pada kondisi rakyat, kita dapat menyusun model pendidikan yang pantas bagi Indonesia. Bagi Ki Hajar, sistem pendidikan Barat yang saklek (konvensional) tak tampak kepribadiannya.
Sebaliknya, menurut Ki Hajar, di Taman Siswa, guru perlu ikut tinggal di sekolah, melebur dengan murid. Tampak seperti suasana keluarga di rumah.
Menurutnya, "Sekolah itu harus pula mendjadi rumahnya guru. Itulah tempat tinggal jang pasti; rumah itu diperuntuki nama guru, atau lebih baik dikatakan orang menjebut pondoknja itu namanja.
Dari dekat dan djauh datanglah murid kepadanja; bukan dia jang pergi ke murid. Kita berkata: ia bukan 'sumur lumaku tinimba' (sumber bedjalan, tempat umum mengambil air). Seluruh suasana paguron itu diliputi semangat pribadinja.
" Menurut beliau, sistem paguron atau asrama itu ada dalam sosok pesantren, yang berabad-abad telah melalui masa bergejolak, tapi tetap hidup hingga kini.
Dalam sistem seperti ini, bukan saja menghendaki pembentukan intelektual, tapi juga, dan terutama, pendidikan dalam arti pemeliharaan dan latihan susila. Pendidikan yang bersuasana kekeluargaan, bukan yang dibeli dan dibayar.
Eksistensi pesantren
Pesantren telah membuktikan eksistensinya di Tanah Air. Pesantren telah ada, setidaknya sejak abad ke-18. Meski pendapat lain menyatakan ia telah ada bahkan sejak Islam berkembang di Nusantara. Berakar dari sistem pendidikan dari Nizhamiyah di Baghdad, pesantren menjadi salah satu ciri khas pendidikan di Nusantara.
Pesantren tak bisa dilepaskan dari peran kiai (ulama). Jaringan ulama di Nusantara memunculkan hadirnya pesantren sebagai lembaga pendidikan di Tanah Air. Para ulama yang berguru ke Makkah dan Madinah kemudian kembali ke Tanah Air untuk membuka pusat-pusat pendidikan (pesantren).
Sudah menjadi kelaziman, santri yang selesai menuntut ilmu kemudian berkelana untuk membuka pesantren.
Setiap pesantren biasanya dikenali kekhasannya. Namun semuanya tetap menggunakan standar rujukan yang sama. (Van Bruissen: 2012).
Meski telah menyebar ke segala penjuru, proses transmisi pengetahuan ini tetap terjaga kualitasnya berkat rantai intelektual yang terjalin antara kiai dan santri, sehingga pesantren telah menjadi pelopor pendidikan di segala penjuru Nusantara, bahkan hingga ke Patani, Selatan Thailand.
Pesantren memungkinkan kiai untuk membimbing para santri, tak hanya saat proses belajar mengajar, tetapi juga di luar waktu tersebut. Dengan membimbing pribadi para santri, kiai mampu mengetahui kelebihan dan kekurangannya.
Sistem pendidikan di pesantren tak hanya mengalirkan ilmu, tapi juga nilai-nilai yang diturunkan kiainya. Ia menjadi pembinaan pribadi terhadap santrinya.
Dengan sistem pemondokan ini, santri meneladani kehidupan kiai bukan hanya di lingkungannya, tetapi juga ketika melebur ke masyarakat.
Pesantren adalah lembaga pendidikan yang tak berjarak dengan masyarakat, bahkan menjadi bagian darinya. Dakwah pesantren dirasakan masyarakat sekitar.
Ia juga menjadi akses bagi segala lapis masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Banyak pesantren yang bahkan mampu menghidupi diri sendiri, dan membuat santri hidup mandiri.
Kebebasan (kemandirian) dari keterikatan karena persoalan finansial ini juga ditekankan Ki Hajar ketika mengelola Taman Siswa. Pesantren bukan saja menjadi penuntun dan pelindung bagi masyarakat, tetapi juga menjadi benteng rakyat Indonesia, dengan menggelorakan perlawanan terhadap kolonialisme.
Pesantren bukan saja menjadi pelindung fisik masyarakat, tetapi juga benteng akidah umat. Sistem pendidikan di pesantren menanamkan nilai-nilai akidah yang kuat, sehingga penjajahan mental dapat dihindari.
Keunggulan pesantren ini adalah dapat berdiri di atas akar yang kokoh. Alih-alih sekadar mengejar permintaan industri atau bentuk pencapaian materi lainnya, pesantren memiliki visi lebih mendalam.
Ulama besar Indonesia yang kiprahnya tak bisa dilepaskan dari kehadiran pesantren di Tanah Air, KH Hasyim Asy'ari, menyoroti peran kiai sebagai figur sentral.
Kebendaan telah begitu menyedot perhatian sehingga kita keliru menata pendidikan. Demi melayani kepentingan kapital dan industri, kita terlampau menaruh perhatian pada materi semata.
Pendidikan telah kita ceraikan dari nilai-nilai agama dan kepedulian kepada lingkungan sekitar. Pendidikan kita telah menjadi sekadar, mengutip istilah Ki Hajar Dewantara, 'dibayar dan dibeli'. ***
Penggiat Jejak Islam untuk Bangsa (JIB)







