Quo Vadis Pelajar dalam Politik Indonesia
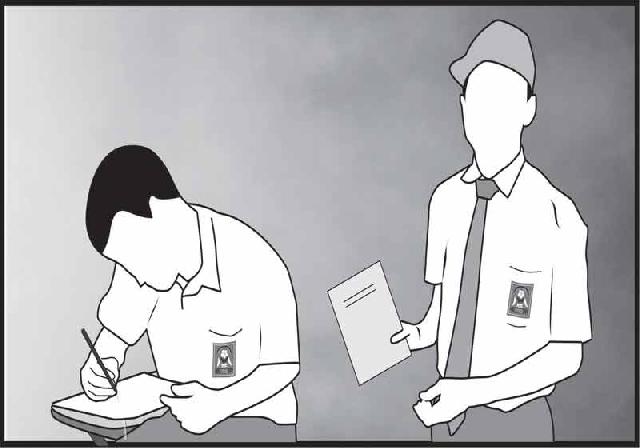
Ketika ada upaya untuk ‘membumihanguskan’ korupsi yang telah membuat pesimis pengelola bangsa ini, maka banyak usulan yang bermunculan bahwa pendidikan tentang bahaya korupsi serta upaya penanggulangannya harus dimulai sejak dini, yakni dari tingkat sekolah lanjutan atas.
Kiranya sosialisasi awal kepada kalangan pelajar akan mampu mengurangi budaya korupsi yang sudah mendarah daging pada bangsa ini.
Demikian wacana yang muncul di tingkat elit bangsa Indonesia. Seolah-olah beban bangsa ini diserahkan kepada pelajar untuk menyelesaikannya, tetapi pada giliran hasil, pelajar dilupakan.
Selain itu, kita juga bisa melihat, pelajar hanya dijadikan sebagai objek politik saja. Pelajar seolah-olah diharamkan untuk terlibat langsung dalam urusan politik. Inilah doktrin yang ampuh di Indonesia. Selama ini, pelajar hanya dikebiri, dituntut untuk ‘manut’ atau ikut saja apa yang dikatakan oleh orang yang lebih dewasa dari mereka.
Kejadian seperti ini tidak hanya di level negara, tetapi juga terjadi pada level keluarga, dimana anak hanya bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tuanya atau adik wajib patuh kepada kakaknya (orang yang lebih tua). Demikian juga halnya di masyarakat, seorang pelajar jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk menyelenggarakan suatu kegiatan di lingkungan masyarakatnya.
Keputusan biasanya diambil oleh para orangtua, namun pada tingkat eksekusi diserahkan kepada remaja atau pelajar setempat. Pelajar dikebiri. Mungkin itulah istilah yang patut untuk kondisi ini.
Pelajar sebenarnya mampu untuk berpikir dan melakukan sesuatu sebagaimana orang dewasa melakukannya. Artinya, batasan umur bukan menjadi persoalan dalam bertindak secara fikiran dan perbuatan.
Usia pelajar adalah saat manusia yang cukup kreatif dalam berpikir. Namun, kekreatifan tersebut memang haruslah disertai pengawasan oleh orang yang lebih dewasa, karena usia mereka juga masa pencarian jati diri. Dulu, bersama teman-tean aktivis mahasiswa, penulis pernah menimbulkan wacana untuk melakukan advokasi dan memperjuangkan menurunkan tingkat usia pemilih pemula dalam proses pemilihan umum dari umur 17 tahun menjadi 15 tahun.
Usia tersebut adalah masa kelas satu di sekolah tingkat atas. Tidak hanya itu, juga berhubungan dengan hak untuk memiliki KTP dan SIM. Keberadaan kalangan pemilih pemula telah menjadi objek kajian politis bagi hitungan setiap pemilu dan pilkada.
Kurang lebih 20 persen pemilih pemula, merupakan generasi muda yang akan menjadi sasaran empuk partai politik dan tokoh politik. Tentu hal ini tidak akan disia-siakan begitu saja, lantaran jumlahnya yang cukup signifikan. Pemilih pemula menjadi ladang emas suara bagi partai politik.
Siapapun itu yang bisa merebut perhatian kalangan ini tentu akan bisa dirasakan keuntungannya. Usulan penurunan batas usia pemilih pemula ini juga itu didasarkan pada lima hal, pertama untuk memperluas demokratisasi dengan memberi kesempatan anak usia 15 tahun keatas untuk menggunakan hak pilihnya. K
edua, mengapresiasi sistem pemilihan langsung dalam pemilu yang merupakan kemajuan demokrastisasi di Indonesia. Ketiga, jumlah mereka yang tergolong anak (usia 15 atau 16 tahun) sangat signifikan, setara dengan 40 kursi di DPR RI. Keempat, banyak permasalahan anak yang bisa diangkat pada agenda politik yang lebih besar. Dan kelima, alasan normatif karena UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah melarang pemanfaatan anak-anak untuk kepentingan politik.
Undang-undang tersebut melarang pelajar dijadikan sebagai objek politik, namun hemat penulis tentulah tidak dilarang jika mereka langsung sebagai pengendali politik (politik praktis). Namun demikian, objek kajian politis ini semestinya tidak berhenti pada kerangka hitungan saja. Jauh lebih mendalam yakni meletakkan komponen ini pada kerangka pendidikan politik yang lebih mencerdaskan. Kini perlu ada pembenahan sudut pandang didalam menempatkan kalangan tersebut pada ruang politik yang lebih luas.
Apa itu? Yakni meletakkan pelajar sebagai subjek pendidikan politik itu sendiri, tidak melulu sebagai objek politik. Selama ini, secara umum pemuda (pelajar) sebagaimana masyarakat umum selalu menjadi objek politik. Mereka hanya dilirik untuk hitungan suara saja. Tidak lebih. Hal ini tentu mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pendidikan politik itu sendiri, yakni pencerdasan politik.
Tidak bermaksud menafikan progress perbaikan kesadaran politik yang ada. Salah satu fakta yang masih bisa ditemui, masih didapatinya pemilih (bukan anak / pelajar) yang sekedar memilih atau asal ikut tanpa diikuti dengan kepahaman dan kesadaran terhadap apa yang dipilihnya. Penggunaan hak politik nampaknya tidak diiringi dengan pendidikan politik yang memadai.
Ini tanggung jawab pelaku politik praktis. Akibatnya bisa dirasakan ketiadaan kesadaran politik yang hadir di setiap partisipasi politik yang mereka lakukan. Hal ini tidak lebih dari sekedar aksi ritual yang lebih mensyaratkan untuk digugurkan, tanpa makna. Semoga bukan sebagai aksi apatisme akut akibat kejenuhan emosional karena sering ditipu oleh para elit partai politik. Selama sudut pandang ini tidak mengalami perubahan, sudah bisa dipastikan hanya akan memicu lahirnya “eksploitasi politik” di kalangan pemilih pemula ini.
Selamanya mereka hanya akan menjadi objek penderita, dan objek kepentingan dari sekelompok golongan yang menginginkan dukungan suara semata. Habis manis sepah dibuang. Ada beberapa hal yang mesti menjadi out put jika umur pemilih pemula ini diturunkan. Pertama, mampu menumbuhkan kesadaran berpolitik sejak dini. Kedua, mampu menjadi aktor politik dalam lingkup peran dan status yang disandang. Ketiga, memahami hak dan kewajiban politik sebagai warga negara secara baik.
Keempat, secara bijak mampu menentukan sikap dan aktivitas politiknya. Disinilah perlu diletakkan secara dini akan arti penting pendidikan politik bagi pemilih (voter education). Dalam kajian kali ini lebih mengarah kepada pendidikan pemilih pemula yang sebagian besar masih duduk di bangku sekolah. Di sadari atau tidak hingga detik ini dunia politik masih meletakkan generasi ini sebagai objek sasar saja. Budaya ini bukanlah kebiasaan sikap yang hadir begitu saja. “Politik bukan urusan pelajar!” Begitu kira-kira kebijakan itu bisa terbaca.
Tentulah kebijakan ini syarat dengan berbagai alasan yang menguntungkan secara sepihak, yakni pemerintah. ***
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab, Pekanbaru







