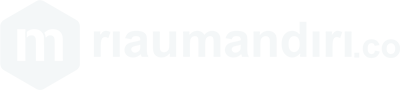Akademisi dan Masyarakat Sipil Beri Rekomendasi Pemulihan Ekologis

Riaumandiri.co - Catatan Koalisi Masyarakat Sipil, persoalan ekologis masih terus berlangsung tiap tahunnya. Dalam kurun waktu 6 tahun saja, terdapat lebih dari 22 korban jiwa meninggal disebabkan banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga serangan harimau.
Belum lagi persoalan kemiskinan akibat pengelolaan lingkungan yang tidak berpihak pada masyarakat. Sayangnya, pemimpin di Riau tidak pernah serius menyikapi persoalan-persoalan yang saban tahun selalu muncul.
Dimulai dari persoalan karhutla, dalam 6 tahun terakhir, Sipongi KLHK mencatat lebih dari 137 ribu ha hutan dan lahan di Riau telah hangus terbakar bahkan menelan 3 korban jiwa pada 2019. Berdasarkan analisis hotspot Jikalahari, 32% karhutla terjadi di areal konsesi HTI dan perkebunan sawit. Setiap tahunnya, pemerintah Riau hanya menetapkan status siaga darurat karhutla dan mengandalkan bantuan dari pusat untuk memadamkan api.
Pada 2024 saja, status siaga darurat karhutla ditetapkan sejak Maret – November 2024. Hanya Kuantan Singingi yang tidak menetapkan status siaga darurat karhutla.
Lain halnya dengan persoalan banjir. Banjir besar melanda Riau di awal 2024. BPBD Riau merilis 233.477 warga Riau menjadi korban terdampak dan lebih dari 61 ribu unit rumah terkena dampak banjir yang terjadi di Riau.
Bahkan banjir di Pekanbaru dan Rokan Hilir menelan korban jiwa, 2 warga meninggal terseret arus banjir pada 2024 dan 4 warga meninggal pada 2019.
Persoalan lingkungan lainnya adalah adanya 13 korban jiwa yang tewas akibat serangan harimau yang kehilangan habitatnya akibat ekspansi perusahaan HTI dan sawit.
Teranyar, pada 4 September lalu warga Sungai Apit di terkam harimau saat istirahat pasca bekerja di kebun. Konflik tak berkesudahan antara harimau dan manusia ini juga dampak dari hilangnya habitat satwa endemik tersebut.
Melihat hal ini, pemerintah Riau juga sama sekali tidak mengeluarkan kebijakan apa pun untuk menyelesaikan persoalan ini, bahkan tidak menunjukkan simpati terhadap para korban.
Persoalan krusial dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan adalah ketidakadilan akses dan hak masyarakat, khususnya masyarakat adat dan tempatan.
Data BPS , jumlah masyarakat miskin di Riau pada 2024 mencapai 492,25 ribu jiwa dan justru tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di kabupaten/kota yang didominasi oleh aktivitas HTI dan sawit seperti Rohul, Kampar, Rohil, Pelalawan dan Kep Meranti .
Koordinator Jikalahari, Okto Yugo Setiyo mengatakan saat ini masih adanya privat sektor yang bentrok dengan masyarakat adat.
Catatan Jikalahari, Okto menyebut sampai hari ini belum adanya pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat, seperti suku Sakai, Talang Mamak dan sebagainya.
"Ketimpangan sektor juga masih terjadi, seperti persoalan privat sektor dengan masyarakat, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, Sakai dan Talang Mamak," ujarnya.
Selain itu, bencana yang ditimbulkan akibat bencana ekologis seperti banjir dan karhutla telah menelan puluhan korban beberapa tahun belakangan.
"Dampak lain dari kerusakan ekologis adalah jatuhnya korban jiwa, misalnya kita kumpulin data dari Bappeda, masyarakat Riau yang meninggal dampak lingkungan yang rusak itu 55 jiwa dari tahun 2018 hingga 2024. 10 orang meninggal karena kebakaran hutan dan lahan, dan rusaknya ruang ekologis akibat konflik satwa harimau dengan manusia, tercatat 13 orang meninggal dunia," ujar Okto.
Jikalahari merekomendasikan kepada Gubernur terpilih yaitu melakukan penataan perizinan korporasi, kemudian mencegah perusahaan untuk tidak melakukan perambahan secara luas.
Akademisi Teknik Sipil Hidroteknik, Dr. Sigit Sutikno, , S.T., M.T menjelaskan bencana banjir yang berada di Pelalawan merupakan dampak dari kerusakan ekologis.
Ia menjelaskan, adanya pengaruh gambut terhadap sulitnya air hujan untuk ditampung oleh tanah.
"Banjir di Pelalawan terjadi setiap tahun, akan semakin besar, coba amati airnya berwarna apa? Merah coklat, itu air. Gambut, air gambut itu 90 persennya air, 10 persennya bahan organik, jadi ketika volume gambut tak mencukupi, lari air itu ke sungai, sungai tidak cukup kapasitasnya, jadi lari ke daratan, mekanismenya begitu," jelasnya.
Lebih jauh lagi, ancaman banjir rob juga sering terjadi di pesisir Riau, seperti Rohil dan Inhil.
Menurutnya, penanaman mangrove perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana banjir rob yang berada di Pesisir Riau.
Keberadaan kawasan mangrove mampu menghasilkan sedimentasi lumpur, dimana pengendapan lumpur yang dihasilkan mangrove tersebut merupakan tanggul alami dalam mencegah banjir rob.
Mangrove mampu menpercepat proses penyerapan air sehingga genangan yang ditimbulkan oleh banjir rob tidak berlangsung lama.
Pakar Sosiologi, Prof Ashaluddin Jalil menilai perizinan HGU suatu perusahaan menyebabkan masyarakat adat menjadi terusir dari rumahnya.
"HTI nanti dapat izin HGU, terus penggundulan hutan, tapi menangis masyarakat adat suku Sakai dan lainnya yang semakin terdesak dan terpinggirkan, ini perlu kita perhatikan," ujar Prof Ashaluddin.
Masyarakat adat yang kebiasaannya bercocok tanam terancam tergerus, hal ini karena hutan alam tempat mereka mencari pangan pun lenyap.
"Hutan alam berburu zona mereka bercocok tanam. Walaupun subsiden, nanti obatan tradisional mereka habis, akses kawasannya juga sulit," ujarnya.
Terakhir, diskusi publik kali ini menghasilkan Policy brief rekomendasi kepada kepala daerah baru, yaitu
1. Mengusulkan kepada Menteri Kehutanan untuk melakukan penataan perizinan kehutanan berupa review perizinan korporasi yang beroperasi di atas lahan gambut, lahan masyarakat hukum adat – tempatan, serta korporasi yang tidak memiliki kemampuan dalam menjaga areal konsesinya dari kerusakan baik karhutla maupun perambahan
2. Memperluas ruang kelola masyarakat dengan memanfaatkan skema perhutanan sosial dan melibatkan masyarakat adat – tempatan sepenuhnya untuk mempermudah proses pengusulan hingga disetujui oleh Kementerian Kehutanan.
3. Menyelesaikan konflik kawasan hutan baik antara masyarakat adat – tempatan dengan korporasi, maupun konflik satwa yang telah kehilangan habitatnya karena ekspansi korporasi yang merusak habitat satwa.