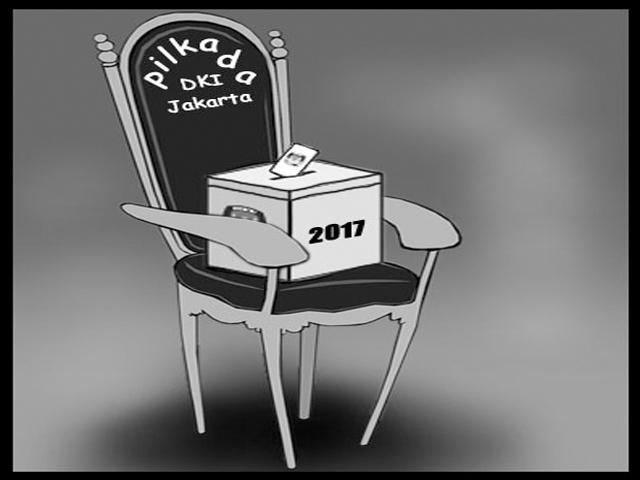PILKADA DKI Jakarta kian dekat. Aroma kompetisi pun sudah terasa menyengat. Sampai saat ini sudah ada calon gubernur (cagub) yang telah resmi dideklarasikan oleh partai politik pengusungnya. Pertama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diusung oleh tiga partai politik, yaitu Hanura, Nasdem, dan Golkar. Kedua, Sandiaga Uno yang baru dicalonkan oleh Gerindra. Mungkin ke depan akan ada lagi calon lain yang didukung oleh di luar keempat partai politik di atas.
Ada yang menarik dianalisis dari keberadaan tiga partai politik yang mengusung Ahok. Tampaknya jumlah tiga partai politik dianggap belum cukup memuaskan mereka, meskipun dari segi persyaratan pencalonan jumlah kursi mereka sudah cukup. Karena itu, mereka merasa perlu untuk mengajak partai politik lainnya untuk bergabung. Hal ini terlihat dari usulan Hanura yang ingin membuat koalisi besar guna memuluskan langkah Ahok untuk kembali memimpin Jakarta. Dalam hal ini, mereka mencoba merayu PDIP agar ikut pula mengusung Ahok.
Jika PDIP bersedia bergabung, tentu koalisi keempat partai politik tersebut akan cukup dominan. Dari sisi jumlah kursi di DPRD DKI, totalnya adalah 62 kursi. PDIP memiliki jumlah kursi terbanyak dengan 28, disusul Hanura 10 kursi, Golkar 9 kursi dan Nasdem 5 kursi. Jumlah keseluruhan kursi di parlemen sendiri adalah 106. Dengan demikian, koalisi pengusung Ahok dapat dikatakan sebagai koalisi besar, apalagi kalau ada partai politik lain yang ikut pula merapat.
Demokrasi Tak Menarik Kalau pada akhirnya koalisi besar yang dikehendaki pengusung Ahok terbentuk dengan masuknya PDIP atau mungkin partai politik lainnya yang kini belum bersikap, maka perhelatan Pilkada DKI pada 2017 nanti bisa jadi tidak akan berlangsung menarik. Demokrasi yang diharapkan dapat terwujud dalam perhelatan politik semacam pilkada menjadi kurang terefleksikan dengan baik karena kompetisi yang terjadi tidak seimbang.
Oleh karena itu, sebaiknya PDIP tidak ikut larut dalam barisan partai politik pendukung Ahok. Apalagi koalisi besar dalam kompetisi politik sebenarnya belum tentu menjamin kemenangan calon yang didukungnya. Dalam kompetisi-kompetisi politik semacam pemilu dan pilkada kerapkali tidak terjadi paralelisme antara suara partai politik dan suara publik. Anomali semacam ini beberapa kali terjadi dalam kompetisi politik di Indonesia baik pada level nasional maupun daerah.
Di samping tidak memberikan jaminan kemenangan, koalisi besar juga salah-salah malah dapat memberikan dampak yang negatif partai-partai politik anggotanya. Mereka akan dianggap publik sebagai partai yang hanya mencari aman semata (safety player) demi meraih kemenangan. Sebaliknya, mereka tidak mau mengambil risiko politik, misalnya, mengalami kekalahan karena berada di luar koalisi besar tersebut.
Koalisi besar juga pada gilirannya akan berdampak pada pascapilkada, yakni adanya ketidakseimbangan hubungan relasional antara eksekutif dan legislatif. Ketika gubernur terpilih berasal dari koalisi besar, maka partai-partai politik di luar koalisi tersenut relatif tidak berdaya pada saat mengemban tugasnya di parlemen. Eksekutif dapat dengan mudah melaksanakan apapun keinginannya karena hampir tidak ada hambatan sama sekali dari kalangan legislatif. Dengan demikian, fungsi checks and balances pun sulit diwujudkan dengan semestinya.
Bagi PDIP sendiri, jika memilih untuk mengajukan calon sendiri, justru akan memeroleh impresi yang positif dari publik. Pertama, kalau PDIP mengajukan calon sendiri, sekalipun berkoalisi dengan partai politik lain, peluang untuk menjadi pemimpin koalisi paling besar. Calon dari PDIP jelas akan ditetapkan sebagai cagub dan wagubnya dari partai politik lain. Dengan memiliki jumlah kursi terbanyak di DPRD tentu partai moncong putih berhak mendapatkan posisi tersebut. Hal ini sulit terjadi jika memilih bergabung mendukung Ahok, selain tidak bisa dominan, juga posisi yang didadaptkannya hanya wagub, karena Ahok sudah dipasang sebagai cagub dengan harga mati.
Kedua, dengan mengajukan calon sendiri PDIP akan dianggap memberikan kontribusi yang positif karena telah memberikan ragam alternatif pilihan politik kepada publik Jakarta. Sebagai kota yang berkarakter multikultural, beragam pilihan yang ditawarkan kepada para penduduknya jelas merupakan solusi yang tepat. Tentu tidak elok kalau publik Jakarta hanya disuguhi dua pasangan calon.
Mencerdaskan.
Di luar itu semua, banyaknya calon yang akan berkompetisi pada Pilkada DKI 2017 nanti justru dapat dipandang sebagai upaya mencerdaskan publik. Dalam konteks demokrasi, publik dituntut tidak hanya sekadar menjatuhkan pilihan begitu saja, tetapi juga mesti menggunakan nalar politiknya. Ada pertimbangan-pertimbangan rasional yang harus dilakukan para pemilih ketika akan menjatuhkan pilihannya. Sebagian besar pemilih Jakarta dapat dikategorikan ke dalam pemilih rasional (rational voters).
Hal tersebut akan sangat mudah terjadi jika pilihan calon pemimpin yang ditawarkan cukup beragam. Para pemilih, dengan demikian, dapat membandingkan antar satu calon dengan calon lainnya dari berbagai aspeknya. Antara lain melalui pelacakan atas rekam jejak (track record) dari setiap calon atau dengan melihat secara cermat program-program kerja yang dikampanyekannnya.
Bagi para kontestan pilkada sendiri, kehadiran kompetitor-kompetitor apalagi yang tangguh seharusnya kian membuatnya terpacu untuk semakin meningkatkan performa dirinya, sehingga mau tidak mau mereka akan bekerja keras agar menjadi yang terbaik. Kompetisi politik yang sehat semacam inilah yang justru sangat diharapkan terjadi dalam pergelaran kompetisi politik seperti pemilu dan pilkada.
Jika Pilkada DKI 2017 berlangsung seperti ini, jelas hal itu akan menjadi peristiwa politik yang mencerdaskan, bukan hanya bagi publik Jakarta, melainkan juga bagi publik Indonesia secara keseluruhan. Bagaimana pun peristiwa politik di Ibu Kota akan selalu dijadikan rujukan oleh kota-kota lainnya di seluruh penjuru negeri ini. Oleh karena itu, kita sangat berharap bahwa Pilkada DKI 2017 bisa menjadi arena pencerdasan publik.***
Penulis adalah Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah.